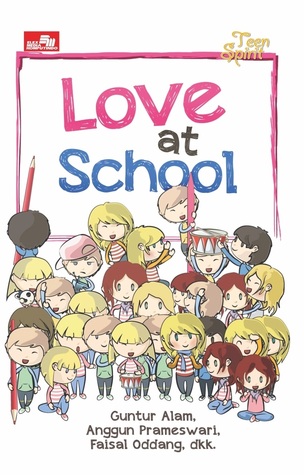Muat di Harian Tribun Jabar, Minggu, 2 November 2014
Tahukah
kau, ada yang terbaring di dasar danau. Seorang perempuan cantik, terlalu
memesona sampai bidadari-bidadari di langit menundukkan kesombongannya. Entah
sejak kapan dia berbaring di sana, di dasar danau yang permukaannya selalu
tenang. Konon hatinya ditikam belati. Bukan belati biasa, melainkan ditempa
dari kesepian panjang. Kesepian yang lahir dari pedihnya ditinggalkan.
Matamu membulat. Setengah percaya. Selebihnya
meremehkan. Wanita di hadapanmu terlalu banyak membual untuk ukuran orang yang
baru dikenal. Kalian sedang berdiri di pinggir danau yang permukaannya lebih
tenang dari ekspresi wajahmu yang selalu datar.
Tidak bisakah wanita ini menceritakan kisahnya
pada orang lain saja?
Ujung gaunnya meliuk diterbangkan angin. Kau bisa
melihat sepasang paha ramping seputih susu. Di kepalamu, pertama yang terlintas
adalah bagaimana raut wajah perempuan itu, jika kau menyentuh sisi paha
dalamnya, sekaligus mengecupnya.
Perempuan
yang terbaring di dasar danau itu tahu, hati siapa saja yang dirundung
kesepian. Kau tahu, kesepian bisa menajamkan telinga? Telinga seperti itulah yang
bisa mendengarkan nyanyiannya.
Kau melemparkan pandangan ke danau. Diam-diam kaucoba
menajamkan telinga. Apa benar ada suara perempuan bernyanyi, mengalun dari
balik permukaan danau? Yang tertangkap inderanya hanya gemerisik angin, suara
daun berjatuhan, dan irama napas wanita di sampingmu. Bagus, batinmu. Baru
bertemu, sudah jadi pembohong.
Namun,
hati-hati. Mendengarnya sekali, kau akan bersuka cita. Kedua kalinya, hatimu
akan terpilin, diingatkan kembali akan kesunyian. Makin kau mendengarnya, makin
kau tak bisa melupakannya. Terikat, tak bisa berpisah dengan yang terbaring di dasar
permukaan danau; yang sesungguhnya tak kalah kesepiannya denganmu.
Kau menghela napas. Wanita ini harus dihentikan.
Dengan wajah tak peduli, kau memanggul softcase
gitar mendahuluinya ke mobil. Entah ide gila siapa yang memasangkanmu dengan
wanita itu. Namun, pementasan segera digelar dan kalian harus berlatih. Dia
penyanyi, kau mengiringinya dengan gitar. Sebatas itulah hubungan kalian.
Namun, saat matamu tertumbuk pada selingkar cincin di jari manisnya, pikiranmu
tak bisa lagi kau kendalikan.
Ada wanita-wanita yang tak boleh kaucintai.
Semacam buah khuldi yang sengaja diciptakan untuk menguji hati. Wanita itu
tersenyum. Senyum itu pun telah beranak pinak di benakmu, cepat persis infeksi
virus, tahu-tahu malam nanti, kau memimpikannya.
Semua orang memanggilnya Senandung. Dan di atas
panggung itu, kau memangku gitarmu. Guyuran lampu sorot melimpah menghujani
Senandung. Kau hanya seorang pendenting gitar; pendamping biduanita yang
menjadi pusat semesta sebenarnya. Tepat pada detik dia melantunkan dendangnya,
kau terbius. Ada perasaan girang, bahagia, rindu, pengharapan; mendesak-desak.
Membuncah. Terlebih saat sesekali, matanya yang sayu ditembakkan ke arahmu.
Jarimu di atas dawai gitar makin menggila, menyesuaikan nada merdunya. Mata
kalian bertautan, persis sorot proyektor yang memutarkan film di benak
masing-masing. Sejak itu, kalianlah bintang
kisah roman kalian sendiri.
***
Sesungguhnya
kau sudah melupakan dongeng perempuan yang terbaring di dasar danau. Namun, selayaknya
wanita itu pandai membuatmu tergila-gila; padahal kau terbiasa membuat perempuan-perempuan
mabuk oleh kecup peluk dan rayu--dia lihai mengingatkanmu kembali pada kisah
itu.
Pagi itu kau dapati dia tercenung. Tangannya
mencengkeram tirai putih yang jendelanya menebarkan pandangan ke arah danau. Dia
mengenakan kemeja putihmu; kebesaran nyaris mencapai setengah pahanya. Kau
bertanya-tanya, apa kemeja itu masih menyimpang aroma peluk kalian semalam.
Pula, apa yang menunggumu jika satu demi satu kancingnya kau lepaskan.
Kau hanya telentang dengan kepala tertopang
lengan, memandanginya. Dia menoleh. Hatimu mencelus, mendapati sepasang matanya
yang digeluti duka.
Seperti
apa sepi yang menemani perempuan yang terbaring di dasar danau itu? Pagi ini,
aku mendengar nyanyiannya. Apa artinya telingaku menajam karena sepi?
Kau bangkit lalu memeluknya dari belakang. Kau
hirup dalam-dalam aroma yang menguar dari tengkuknya.
“Bicara apa kau ini? Ada aku. Bagaimana kau bisa
kesepian?”
Aku
selalu membayangkan dada perempuan di dasar danau itu mengeras ditancap belati.
Seperti dadaku kini. Beku oleh sepi, keras oleh sunyi. Dan pagi ini aku
dibangunkan oleh lantunan suaranya.
Bahkan detik itu juga, kau masih belum
menganggapnya gila. Kau memandanginya dengan limpahan kasih, memagut bibirnya
yang dingin.
“Ada aku yang mencintaimu. Masih kurang apalagi?”
Bagaimana
kalau kau meninggalkanku? Kau lelaki pemuja kebebasan. Tak ada satu peluk
perempuan pun yang sanggup mengikatmu. Belum lagi aku wanita dengan naluri
merawat, itu akan membuatmu sesak suatu hari.
Mungkin harus ada yang menamparmu. Memberitahumu, bahwa
kali ini kau jatuh cinta pada wanita berisi kepala rumit.
Belum
lagi aku wanita dengan rumah untuk pulang. Bagaimana jika suatu hari aku yang
akan meninggalkanmu? Kau akan berkubang dalam kesepian. Telingamu akan tajam
karena duniamu terlalu sunyi. Kau akan mendengar nyanyian perempuan yang
terbaring di dasar danau itu. Dia akan memintamu mengiringinya bernyanyi.
Kau melonggarkan pelukan dan membalikkan tubuhnya.
Baru kali ini kau mendapati matanya yang sesungguhnya terbuat dari kristal. Dekapanmu
kali ini lebih erat. Benar, sayup-sayup kau mendengar ada yang bernyanyi di
kejauhan. Jauh sekali, rasa-rasanya seperti berasal dari dasar danau.
***
Kini kau dan dia berdiri berdampingan di susuran
setapak di pinggir danau. Kalian tak berani saling menatap. Ada yang runcing
hendak menancapi bola matanya. Siap meledak.
Kau
bisa dengar yang sekarang kudengar? Kadang aku bertanya, lelaki mana yang tega
menancapkan belati kesunyian di dadanya. Jika mencintai ternyata menyakitinya
sedemikian rupa, apakah lebih baik sedari awal mematikan rasa?
Kau tak menjawab. Matamu lurus menatap bola
matanya bergulung-gulung persis mendung yang nyaris pecah jadi hujan. Selama
ini, kau mengenal perempuan sebagai taklukan. Kau bertemu, bermanis kata dengan
bius mata, bercinta tanpa melibatkan hati, dan berlalu begitu saja keesokan
pagi. Wanita ini berbeda. Selalu memperumit segalanya. Bahkan sampai hatimu tak
lagi sanggup mengikutinya. Namun, bukankah hati memang tak sesederhana
persamaan matematika?
“Kita masih bisa saling mencintai dan bersama,”
katamu. “Walaupun aku pemuja kebebasan dan kau wanita yang mempunyai rumah
untuk pulang.”
Cinta
apa yang seperti itu? Kita bisa saja bercinta berkali-kali, tapi di penghujung
hari kita kembali bergelung sepi. Bukan seperti itu cinta yang kucari.
“Lalu apa? Kenapa cintamu rumit sekali?” kau
setengah membentak.
Kau
sederhana. Aku rumit. Itulah yang membuat kita tak saling memiliki. Itulah
kenapa aku sering merasa kosong, bila bersamamu. Dan telingaku sudah lelah
mendengar nyanyian perempuan yang terbaring di dasar danau.
Lama mereka bertatapan. Dalam tarikan napas
kesekian, dia menghambur ke pelukmu. Kau menariknya seperti kubangan pasir
isap. Pada bibir yang saling bersentuhan, kalian menuliskan kenangan. Kau
melihatnya memagutmu dengan mata terpejam dan air mata berlinangan. Tepat saat
dia menarik bibirnya lepas, ada retak di dadamu. Sebuah belati dia tikamkan di
sana.
Untuk pertama kalinya, bukan sayup-sayup lagi, kau
kini jelas mendengar suara merdu itu. Rasa-rasanya seperti dari dasar danau di
hadapanmu. Jadi perempuan yang terbaring di dasar danau itu benar ada?
***
Entah sudah pagi ke berapa kau mendapati dirimu
berdiri di sini. Mencengkeram susuran pembatas danau dan jalan setapak.
Malam-malam sebelumnya kau terjaga. Sepertinya wanita itu pergi dengan membawa
kantukmu. Kauhabiskan waktu menulis banyak lagu. Ratusan lirik. Seakan kepalamu
adalah sumur yang terus meluapkan lumpur. Orang-orang bilang kau patah hati.
Namun, kau tahu betul, hatimu tak sekadar patah. Hatimu jatuh pecah. Kepingnya
berhamburan, terserak angin ke segala arah.
Kau dipeluk kesepian yang tak kau ketahui di mana
ujungnya. Benar, kesepian menajamkan telinga. Kau pun mulai menangkap lantunan
merdu dari kejauhan. Sangat jauh, seakan berasal dari dasar danau.
Lama-lama suara itu nyata. Seakan asalnya dari
hatimu sendiri. Mungkin sesungguhnya hatimu dan danau itu serupa. Di dasarnya
sama-sama didiami oleh seseorang yang terbaring dengan luka tikam di dada. Di
danau, ada perempuan itu. Di hatimu, ada kau sendiri.
Kau mulai melangkah. Mengawang tak bisa kau
kendalikan. Kau menuruni ujung susuran yang tersambung ke arah pinggir danau.
Suara itu tak kasat mata. Tapi kau bisa merasakan ada jerat yang membungkus
tubuhmu.
Mungkin ketimbang sepi sendiri, kau merasa lebih
baik sepi berbagi. Tak kau pedulikan lagi basah yang makin menyergap. Danau itu
perlahan merentangkan tangannya. Menawarkan pelukan. Menelanmu pelan-pelan.
Tepat saat kau tak tersentuh udara lagi, kau bertekad untuk mengiringi
perempuan yang terbaring di dasar danau itu dengan denting gitarmu. Karena kau
tahu, kesepian lebih baik bila dibagi.
***
Ada sepasang muda-mudi berangkulan. Keduanya
terbius menatap lembayung yang berhamburan di langit. Sang pemuda menoleh ke
arah gadisnya. Ada yang tergenapi dalam hatinya saat melihat senyum mengembang
di bibir ranum itu.
“Kau tahu mitos di danau ini?” tanya gadis itu
menoleh cepat.
“Siapa yang tidak tahu? Kalau ada sepasang kekasih
kemari, maka hubungan mereka akan kandas. Karena kutukan perempuan yang
terbaring di dasar danau.”
“Banyak juga yang bunuh diri di sini karena patah
hati,” sambung si gadis menatap kekasihnya lekat. “Kalau aku meninggalkanmu,
apa kamu akan bunuh diri?”
“Kamu sendiri?”
Keduanya melemparkan pandangan ke arah permukaan
danau yang tenang. Benak mereka penuh oleh banyak hal. Riuh oleh gelora cinta
yang teredam oleh sekadar genggaman tangan.
Tanpa mereka sadari, sayup-sayup terdengar
lantunan suara. Seakan berasal dari tempat di kejauhan, tapi juga dekat.
Mungkin dari dasar danau; atau dari dasar hati, tempat segala kesunyian
bermuara.
***